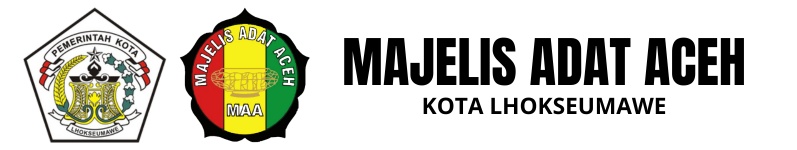DOWNLOAD
- Beranda
- Unduhan
Berikut Data atau File yang dapat Anda unduh
| No | Judul | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| 1 | hasil Kesimpulan Seminar Sejarah kota Lhokseumawe | hasil seminar kota lhokseumawe |
Unduh |
| 2 | Makalah Peradilan Adat | PERADILAN ADAT; GAMPOENG IDEAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETAN DENGAN ADIL DAN BERMARTABAT (Refleksi pelaksanaan Kegiatan Penguatan Peradilan Adat, MAA Kota Lhokseuamwe–2025) Oleh Dr. Usammah, M. Hum (Ketua Bidang Hukum Adat MAA Kota Lhokseumawe) ========================================================== Pendahuluan Gampong (desa) bukan sekadar satuan administratif dalam struktur pemerintahan Indonesia. Ia adalah ruang hidup masyarakat yang menyimpan nilai-nilai luhur, tradisi, serta jati diri sebuah komunitas. Di Aceh, gampong memiliki makna yang lebih dalam, karena ia menjadi pusat peradaban kecil yang masih mempertahankan kearifan lokal, termasuk dalam hal penyelesaian konflik sosial melalui peradilan adat. Peradilan adat merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga harmoni sosial dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal. Di Aceh, misalnya, eksistensi peradilan adat tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga secara hukum melalui payung regulasi yang memperkuat kedudukannya dalam sistem pemerintahan gampong. Peradilan ini menjadi sarana penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, kedamaian, dan keadilan berbasis nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Peradilan adat merupakan bagian dari sistem sosial tradisional yang berfungsi dalam menyelesaikan konflik dan menjaga ketertiban masyarakat berdasarkan nilai-nilai lokal. Keberadaan peradilan adat di Aceh telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat gampong. Bahkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara eksplisit mengakui eksistensi dan kewenangan peradilan adat, di tambah dengan adanya qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yang secara sosiologis kehidupan masyarakat Aceh regulasi tersebut menjadi pegangan dalam kehidupan sosial dan menyelesaikan setiap masalah. Peradilan adat bukanlah sistem hukum yang kaku dan bersifat represif. Ia merupakan bagian dari sistem sosial yang bersifat inklusif dan humanis, yang bertumpu pada prinsip musyawarah, keadilan, dan pemulihan hubungan antar warga. Perkara-perkara seperti sengketa tanah, perkelahian antar warga, pelanggaran norma sosial, hingga persoalan rumah tangga kerap diselesaikan melalui mekanisme adat yang melibatkan tokoh masyarakat, tuha peut, dan aparatur gampong. Di tengah berbagai tantangan modernisasi dan dominasi sistem hukum formal, keberadaan peradilan adat menjadi harapan tersendiri bagi masyarakat akar rumput (menengah kebawah). Ia mampu menjawab kebutuhan akan keadilan yang cepat, murah, dan berorientasi pada keharmonisan sosial. Sementara sistem hukum negara sering kali dianggap jauh, lambat, dan tidak memahami konteks budaya lokal, peradilan adat justru hadir sebagai solusi yang membumi dan dapat diterima oleh semua pihak. Impian gampong bermartabat adalah impian tentang masyarakat yang hidup dalam harmoni, yang memuliakan hukum namun tidak melupakan akar budayanya. Martabat sebuah gampong tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur atau program pembangunan, melainkan oleh kemampuan masyarakatnya dalam menjaga nilai-nilai keadilan, kedamaian dan persatuan, dalam konteks ini, peradilan adat menjadi pilar penting dalam menjaga martabat tersebut Namun demikian, mewujudkan peradilan adat yang ideal tidak bisa dilepaskan dari sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat tumpang tindih antara kewenangan peradilan adat dan peradilan negara. Kedua, kapasitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi adat sering kali terbatas dari segi pemahaman hukum maupun administrasi. Ketiga, belum semua masyarakat memahami atau menghargai mekanisme adat sebagai bentuk penyelesaian yang sah dan bermartabat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk merevitalisasi peran peradilan adat dalam mewujudkan gampong bermartabat. Ini mencakup pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur adat, harmonisasi peraturan adat (qanun Aceh) dengan hukum nasional, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa berbasis nilai lokal. Pemerintah, lembaga adat dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menjaga dan mengembangkan sistem peradilan adat yang adil, akuntabel dan responsif terhadap dinamika sosial. Sebagaimana pepatah Aceh menyebutkan, “Adat bak po rumoh, hukom bak uteun; bek meulet bak ngon seunanyan” (Adat seperti pagar rumah, hukum seperti hutan; jangan disamakan, tapi harus diselaraskan). Pepatah ini menggambarkan pentingnya kolaborasi antara sistem hukum negara dan kearifan lokal dalam menjaga ketertiban sosial. IImpian Gampong Bermartabat melalui Peradilan Adat tidak sekedar hanya sebagai slogan, tetapi sebuah visi strategis untuk membangun sistem keadilan sosial yang mengakar di tengah masyarakat. Ini adalah upaya untuk merestorasi nilai-nilai gotong royong, keadilan restoratif, serta identitas kultural yang selama ini menjadi ruh kehidupan masyarakat gampong. Melalui revitalisasi peran dan fungsi peradilan adat, diharapkan gampong tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang hidup yang bermartabat, berkeadilan dan harmonis. Dengan memperkuat peradilan adat, kita tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga membangun pondasi keadilan yang lebih manusiawi dan berakar. Inilah wajah impian gampong bermartabat—gampong yang tak hanya membangun fisik, tapi juga nilai dan jiwa warganya. Rumusan Masalah
Tujuan Penulisan
Pembahasan
Peradilan adat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya di wilayah yang masih kental dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti di Aceh. Di tingkat gampong (desa), peradilan adat memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan berbasis musyawarah dan mufakat. Mekanisme ini menjadi solusi alternatif terhadap sistem peradilan formal yang sering kali dianggap jauh, lambat, dan tidak sepenuhnya memahami konteks sosial-budaya lokal. Peradilan adat adalah lembaga penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada hukum adat setempat. Di Aceh, keberadaan peradilan adat diakui secara hukum melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Disebutkan dalam Pasal 5 bahwa tujuan adanya qanun tersebut antara lain; (a) menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis; (b) tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat; (c) membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat; (d) memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat; (e) merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh; dan (f) menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.[1] Peradilan adat di gampong berperan sebagai forum rekonsiliasi dan pemulihan, bukan penghukuman. Tokoh-tokoh adat seperti keuchik, tuha peut, dan tokoh agama biasanya memimpin proses ini dengan pendekatan restoratif.[2] Di tingkat gampong, peradilan adat biasanya dilaksanakan oleh perangkat gampong seperti keuchik, tuha peut, tokoh adat, dan tokoh agama. Prosesnya menekankan pada prinsip keadilan restoratif (restorative justice), di mana pelaku dan korban didamaikan dengan pendekatan kekeluargaan. Adapun yang menjadi peran strategis dari peradilan adat, antara lain;
Peradilan adat berperan sebagai sarana penyelesaian konflik secara cepat, damai, dan tidak berlarut-larut. Hal ini mencegah terjadinya eskalasi konflik yang bisa mengganggu stabilitas sosial. Kasus-kasus seperti perselisihan keluarga, sengketa batas tanah, atau pelanggaran norma adat dapat diselesaikan tanpa melibatkan aparat penegak hukum formal.
Peradilan adat memungkinkan masyarakat menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan hemat biaya dibanding sistem peradilan formal. Tidak adanya biaya perkara serta pendekatan berbasis musyawarah menjadikan forum ini inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk masyarakat miskin dan kurang terdidik. Selain itu, karena dilakukan di lingkungan sosial yang sama, proses ini tidak menimbulkan jarak antara pihak bersengketa dan penyelesai masalah. “Peradilan adat menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang cepat dan efisien, serta berbasis kearifan lokal”.[3]
Sistem peradilan formal sering kali tidak mampu menangkap nuansa sosial-budaya setempat. Peradilan adat hadir dengan pemahaman mendalam terhadap nilai dan norma lokal, sehingga mampu menghasilkan putusan yang lebih diterima masyarakat. Hal ini memperkuat rasa keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.[4] Adat memiliki fungsi sebagai “social control” yang sangat efektif dalam masyarakat tradisional.
Peradilan adat menjaga eksistensi budaya hukum lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Ini sangat penting dalam membangun identitas dan karakter masyarakat gampong yang berlandaskan nilai-nilai gotong royong, saling menghormati, dan keadilan sosial.
Dengan menyelesaikan sengketa-sengketa kecil secara lokal, peradilan adat mengurangi beban peradilan negara dan mendorong penyelesaian sengketa secara efisien. Hal ini juga sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, khususnya dalam konteks keistimewaan Aceh.[5] 6. Memberdayakan Struktur Sosial GampongPeradilan adat memperkuat peran dan fungsi tokoh-tokoh lokal seperti keuchik, tuha peut, dan tokoh adat lainnya. Dengan aktifnya peradilan adat, struktur sosial gampong menjadi lebih fungsional dan berwibawa dalam menyelesaikan persoalan. Hal ini turut memperkuat pemerintahan gampong yang partisipatif dan berorientasi pada penyelesaian masalah bersama. Pemerintah Aceh melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “lembaga adat adalah mitra pemerintah gampong dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga ketertiban masyarakat.”⁵ B. Peradilan Adat sebagai Pilar Keadilan Sosial di GampongPeradilan adat merupakan bentuk keadilan partisipatif. Proses penyelesaiannya tidak hanya memperhatikan aspek legalitas, tetapi juga nilai-nilai budaya, norma sosial, dan keterikatan emosional antarwarga. Dalam banyak kasus, peradilan adat mampu meredam konflik sebelum membesar, dan mencegah fragmentasi sosial [6] di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya peradilan adat yang aktif dan dihormati, gampong mampu menjaga stabilitas sosial, memperkuat identitas lokal, dan menanamkan rasa keadilan secara kolektif. Inilah yang menjadi fondasi dari gampong bermartabat: masyarakat yang tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga terikat oleh nilai, rasa, dan tradisi yang menjunjung perdamaian. Dalam Pasal 98 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa penyelesaian perkara adat dilakukan oleh lembaga adat sesuai dengan hukum adat dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hak asasi manusia.
C. Strategi penguatan peradilan adat dalam mewujudkan gampong yang bermartabatPeradilan adat merupakan instrumen penting dalam tata kelola sosial masyarakat di tingkat gampong. Di Aceh, peradilan adat tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme pelestarian nilai-nilai budaya, keadilan restoratif,[7] dan solidaritas sosial. Dalam konteks gampong bermartabat yaitu gampong yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan dan harmoni sosial, peradilan adat memainkan peran kunci. Namun, dalam praktiknya, peradilan adat menghadapi berbagai tantangan: ketidakpastian hukum, keterbatasan SDM, kurangnya dokumentasi, hingga rendahnya partisipasi generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan strategi konkret untuk memperkuat lembaga ini agar dapat berperan optimal dalam mewujudkan masyarakat gampong yang adil, damai, dan bermartabat, antara lain;
UUD 1945 Pasal 18.B telah mengakui eksistensi kelembagaan masyarakat adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat, didukung oleh Qanun No. 9/2008 dan Qanun No. 10 /2008, ditambah dengan dukungan dari qanun dan peraturan lainnya dari Bupati / Walikota. Penguatan hukum adat perlu diorientasikan pada sinkronisasi dengan sistem hukum nasional agar tidak terjadi dualisme kewenangan”.[8] Penguatan yang dilakukan seperti;
Sebagian besar aparat adat dan perangkat gampong belum memiliki pelatihan hukum, mediasi, atau administrasi yang memadai. Padahal, untuk menjalankan peradilan adat secara adil dan efisien, diperlukan kompetensi dasar dalam hukum dan manajemen perkara. Strategi peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui:
Salah satu kelemahan terbesar peradilan adat adalah tidak adanya dokumentasi yang tertib dan berkelanjutan. Akibatnya, keputusan adat tidak memiliki nilai administratif maupun kekuatan hukum dalam sengketa yang lebih besar, serta sulit dijadikan rujukan dalam pendidikan hukum masyarakat. Untuk menjawab tantangan ini, strategi digitalisasi perlu didorong, seperti:
“Sistem dokumentasi yang baik akan memperkuat kepercayaan publik dan menjadikan peradilan adat bagian dari sistem tata kelola yang transparan dan profesional”.[9] 4) Sinergi antara Peradilan Adat dan Lembaga Hukum FormalPeradilan adat tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dan pengakuan dari aparat hukum formal seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja sama dan koordinasi yang jelas antara kedua sistem ini. Langkah strategis yang bisa diambil antara lain:
5) Penguatan Pendidikan dan Sosialisasi Nilai-Nilai AdatStrategi ini penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, terutama generasi muda, terhadap nilai-nilai adat dan pentingnya keadilan berbasis budaya. Modernisasi dan gaya hidup individualistik telah menyebabkan nilai-nilai adat mulai terpinggirkan. Langkah-langkah yang bisa ditempuh:
6) Monitoring, Evaluasi, dan Insentif bagi Praktik Peradilan Adat yang BaikAgar peradilan adat tidak disalahgunakan atau dijalankan secara diskriminatif, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang independen. Ini bisa dilakukan oleh lembaga adat tingkat kabupaten, akademisi, atau lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, insentif dan apresiasi juga dapat diberikan kepada gampong yang berhasil mengelola peradilan adat secara efektif. Misalnya dalam bentuk:
7) Tantangan dalam Penguatan Peradilan AdatBeberapa tantangan yang dihadapi antara lain:
D. Bentuk Peradilan Adat GampoengPeradilan adat di Aceh memiliki struktur yang unik dan berlapis sesuai dengan tatanan pemerintahan gampong hingga tingkat mukim dan kabupaten/kota. Peradilan ini dijalankan berdasarkan adat istiadat Aceh yang hidup dan dihormati masyarakat.Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 60 Tahun 2013 mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara adat di Aceh. Pergub ini bertujuan untuk memperjelas dan memberikan landasan hukum bagi peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat Gampong.Isi Pokok Pergub Aceh No. 60 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Adat; Pergub ini mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, termasuk tingkatan peradilan, jenis perkara, dan prosedur yang harus diikuti.
Putusan peradilan adat dianggap bersifat damai dan mengikat, yang berarti jika suatu perkara sudah diselesaikan melalui peradilan adat, maka tidak dapat diajukan lagi ke peradilan umum, kecuali ada hal-hal khusus yang diatur dalam peraturan tersebut.
Pergub ini juga memperjelas peran lembaga adat, seperti Keuchik, Tuha Peut, dan pimpinan adat lainnya dalam proses penyelesaian perkara adat.
Terdapat ketentuan khusus mengenai penyelesaian sengketa yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, yang dilaksanakan secara tertutup di rumah pimpinan adat.
Pergub ini secara tidak langsung memperkuat otonomi gampong dalam menyelesaikan masalah internal mereka melalui peradilan adat.
Pergub ini juga memuat asas-asas peradilan adat, seperti terpercaya, bertanggung jawab, kesetaraan, cepat, mudah, murah, ikhlas, sukarela, dan penyelesaian damai.
Dengan adanya Pergub ini, diharapkan penyelesaian sengketa di Aceh dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku.E. Penutup.1. Qanun Adat Aceh adalah perangkat hukum yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Aceh, memastikan pelaksanaan syariat Islam dan nilai-nilai adat dalam berbagai aspek kehidupan, serta memberikan wadah bagi penyelesaian sengketa dan pembinaan adat.2. Dengan adanya Qanun Peradilan Adat, diharapkan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh dapat terus terjaga, serta penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efektif dan bermartabat3. Peradilan adat memainkan peran penting dalam membangun keadilan sosial dan menjaga martabat gampong. Ia menawarkan model penyelesaian sengketa yang kontekstual, partisipatif, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Mewujudkan gampong bermartabat berarti menghidupkan kembali peradilan adat sebagai ruang keadilan yang humanis dan inklusif. Namun, tantangan berupa dualisme hukum, minimnya pengakuan formal, dan lemahnya kapasitas kelembagaan perlu segera diatasi melalui strategi yang kolaboratif.REFERENSI1. Asshiddiqie, Jimly. (2009). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press2. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Laporan Tahunan Mahkamah Agung: Penguatan Keadilan Restoratif Melalui Lembaga Adat3. Sulaiman. (2015). Hukum Adat di Aceh: Antara Pelestarian dan Tantangan Modernisasi. Banda Aceh: Pustaka Rakyat4. Sumardjono, Maria S.W. (2009). Hukum dan Keberlanjutan Sosial: Peran Hukum dalam Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press5. Sumardjono, Maria S.W. (2009). Hukum dan Keberlanjutan Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press6. Zainuddin, H. (2018). Efektivitas Peradilan Adat dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif di Aceh. Prosiding Seminar Nasional Adat dan Hukum, Universitas Malikussaleh7. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kelembagaa Adat dan Istiadat, Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008, Nomor 09.BIODATA DIRI
N a m a : Dr. Usammah, M.Hum Tempat / Tgl. Lahir : Lhokseumawe / 14 Maret 1969 Jenis Kelamin : Laki-laki Status : Kawin A g a m a : Islam A l a m a t : Jln. T. Nyak Arif No. 92 Komplek Bukit Panggoi Indah Mns. Mesjid Kecamatan Muara Dua – Lhokseumawe Nomor Kontak : 08116856919 Alamat email : sammah0369@gmail.com WA : 08116856919 (usammah) Facebook : Usah Mah
Sidang Promosi Tanggal 28 Desember 2016, Dengan Judul Disertasi “Takzir sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Kajian Terhadap Penerapan Qanun Jinayat Tahun 2014)
Penulis;
Dr. Usammah, M. Hum
[1] Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kelembagaa Adat dan Istiadat, Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008, Nomor 09. [2] Sulaiman. (2015). Hukum Adat di Aceh: Antara Pelestarian dan Tantangan Modernisasi. Banda Aceh: Pustaka Rakyat [3] Sumardjono, Maria S.W. (2009). Hukum dan Keberlanjutan Sosial: Peran Hukum dalam Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press [4] Zainuddin, H. (2018). Efektivitas Peradilan Adat dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif di Aceh. Prosiding Seminar Nasional Adat dan Hukum, Universitas Malikussaleh [5] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Laporan Tahunan Mahkamah Agung: Penguatan Keadilan Restoratif Melalui Lembaga Adat. [6] Kondisi di mana sebuah masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang terpisah dan kurang terhubung satu sama lain, Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan ekonomi, etnis, agama, atau ideologi, yang menyebabkan kurangnya kohesi sosial dan interaksi antar kelompok [7] Pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak, bukan hanya pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini melibatkan dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan keadaan seperti semula. [8] Asshiddiqie, Jimly. (2009). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press [9] Sumardjono, Maria S.W. (2009). Hukum dan Keberlanjutan Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press |
Unduh |